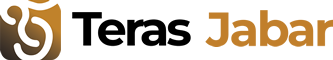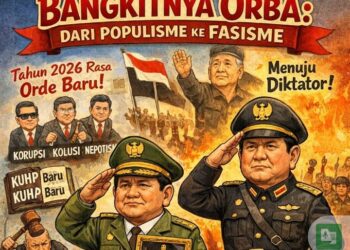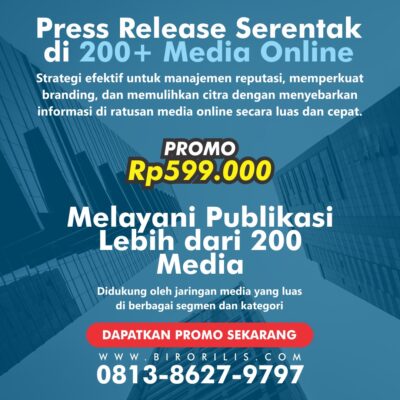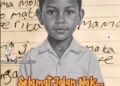Oleh: HMU Kurniadi
Peneliti senior IDEALS
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto selalu mengundang perdebatan panas. Di satu sisi, ia dianggap Bapak Pembangunan yang membawa Indonesia keluar dari kekacauan pasca-G30S. Namun di sisi lain, ia juga dicatat sebagai penguasa otoriter yang menumpas lawan politik, membungkam kebebasan, dan memperkaya kroninya. Dua wajah Soeharto inilah yang membuat pertanyaan “pantaskah?” terus menggantung di ruang publik.
Perdebatan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kian memuncak setelah Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf secara resmi mengajukan 49 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional, yang salah satunya Soeharto, kepada Presiden Prabowo melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang diketuai Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon pada 5 November 2025. Bisa jadi apabila dipaksakan, gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden itu akan ternoda kesakralannya dengan digugat ke meja hijau.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menegaskan, Pahlawan Nasional adalah sosok yang berjasa luar biasa, berkorban demi bangsa, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangan. Artinya, kepahlawanan bukan hanya diukur dari hasil pembangunan, tetapi juga dari integritas moral dan kemurnian pengabdian.
Dalam teori sosial, ada dua lensa utama menilai pahlawan. Pertama adalah heroisme moral yakni menempatkan kejujuran, pengorbanan, dan keberanian membela kebenaran sebagai inti kepahlawanan. Yang kedua adalah heroisme pragmatis yakni menilai pahlawan dari manfaat konkret bagi masyarakat, meski cara yang ditempuh bisa penuh kompromi dan kekerasan. Soeharto, tanpa diragukan, hidup di persimpangan dua teori itu.
Dalam teori klasik, Thomas Carlyle (1841) melalui bukunya On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History berpendapat bahwa pahlawan adalah individu luar biasa yang mengubah jalannya sejarah melalui kekuatan moral dan keteladanannya.
Namun teori modern seperti Philip Zimbardo (2007) dalam The Lucifer Effect memperluas konsep pahlawan sebagai individu yang berani melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu dilakukan melawan sistem yang berkuasa.
Sementara itu, Ernest Becker (1973) dalam The Denial of Death menyebut pahlawan sebagai figur yang menolak kefanaan dengan menciptakan makna abadi bagi masyarakatnya. Dengan demikian, kepahlawanan tidak hanya diukur dari hasil pembangunan, tetapi juga dari dimensi moralitas dan kemanusiaan.