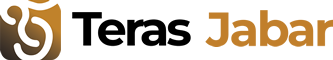Oleh Subchan Daragana
Ada masa ketika rasa ingin tahu adalah tanda kecerdasan. Orang yang ingin tahu dianggap hidup, kritis, dan terbuka. Tapi di zaman digital ini, rasa ingin tahu sering berubah jadi candu. Kita tidak lagi ingin tahu untuk memahami, tapi untuk membandingkan, menilai, bahkan menelanjangi. Dunia maya memelihara budaya baru — kepo brutal — di mana rasa ingin tahu kehilangan malu, dan komunikasi kehilangan jarak.
Kata “kepo” dulu hanya bahasa gaul yang lucu. Asalnya dari Hokkien “kay poh” (雞婆), berarti orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Dalam bahasa Mandarin, “ji po” berarti wanita cerewet yang selalu ingin tahu urusan orang.
Tapi di Indonesia, maknanya berubah: kepo tidak selalu berarti negatif, kadang malah dianggap lucu, bahkan identitas sosial. “Aku kepo banget sama dia,” bisa berarti ingin tahu karena penasaran, empati, atau sekadar ikut tren percakapan. Namun ketika rasa ingin tahu itu tidak lagi dibingkai oleh nilai, ia berubah menjadi invasi — penyerbuan ke ruang pribadi yang dulu dianggap tabu.
Secara budaya, masyarakat Nusantara punya tradisi komunikasi yang penuh rasa. Ada tepa selira, ada rasa malu, ada eling lan waspada — semua mengajarkan kesadaran untuk tidak melampaui batas orang lain. Orang dulu bertanya dengan halus, menyapa dengan tatakrama. Tapi di era digital, semua batas itu mencair. Algoritma membuka tirai kehidupan orang lain, dan tanpa sadar, kita semua jadi penonton yang menilai. Privasi berubah jadi tontonan, dan kepo jadi gaya hidup.
Di sini, kepoan bukan lagi tanda ingin tahu, tapi tanda kehilangan arah tahu. Orang ingin tahu bukan karena ingin memahami, tapi karena takut ketinggalan. Fear of missing out — FOMO — itulah agama baru dunia digital. Setiap unggahan orang lain seperti bisikan: “Lihat, hidupku lebih seru dari hidupmu.” Maka orang membuka gawai bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk menenangkan rasa tidak cukup. Kita scroll tanpa sadar, mencari validasi bahwa kita masih relevan, masih diperhatikan, masih dianggap ada.
Secara psikologis, kepoan adalah cermin dari kekosongan diri. Ia tumbuh dari perasaan tidak aman, dari keinginan membandingkan diri dengan orang lain. Konsep social comparison yang pernah dijelaskan Leon Festinger (1954) kini terjadi setiap detik di layar ponsel kita. Kita menilai diri lewat pantulan hidup orang lain, padahal yang kita lihat hanyalah versi terkurasi dari realitas.
Hidup orang lain tampak sempurna karena mereka hanya menampilkan yang layak ditonton. Sementara kita, menonton sambil merasa kalah. Ironisnya, semakin sering kita kepo, semakin hampa kita rasakan — karena yang kita cari sebenarnya bukan kabar orang lain, tapi pengakuan atas diri sendiri.