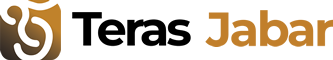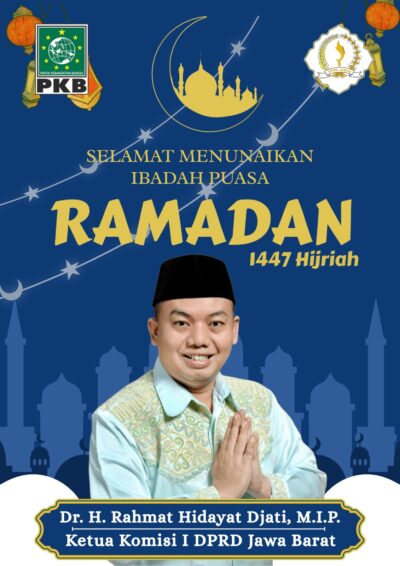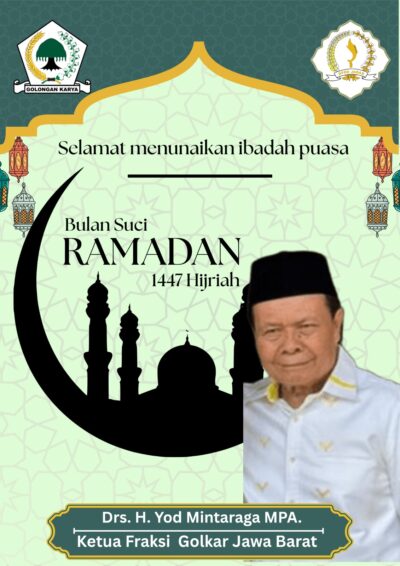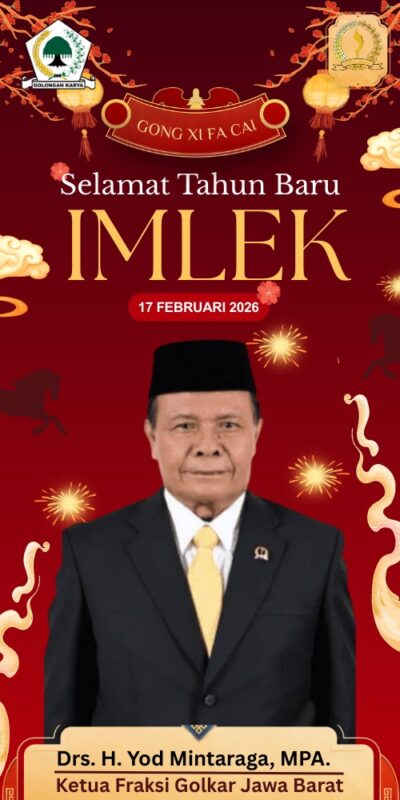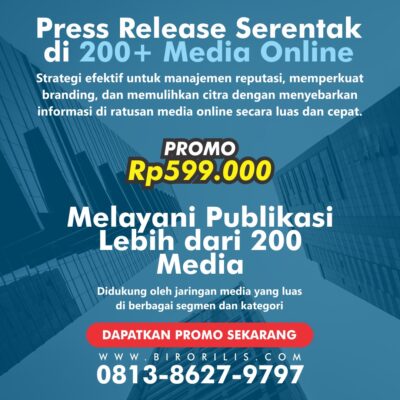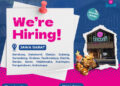Kecepatan digital inilah yang secara perlahan melahirkan budaya instan. Nilai hidup direduksi menjadi hasil cepat, pujian cepat, dan pencapaian cepat. Banyak anak muda tumbuh dalam dunia di mana keberhasilan diukur dari seberapa cepat sebuah video viral, seberapa cepat konten mendapatkan “like”, atau seberapa cepat orang lain menoleh. Ketika semuanya terjadi dengan instan, gagal menghadapi realitas yang tidak instan akan melahirkan kegelisahan. Kekecewaan kecil terasa besar. Ujian kecil terasa berat. Kritik kecil terasa serangan pribadi. Itulah yang disebut para psikolog sebagai generasi bermental rapuh. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia terlalu cepat, terlalu bising, dan terlalu menuntut.
Media sosial memperkuat kondisi ini dengan menghadirkan dramologi emosi istilah dari pemikiran Virilio tentang bagaimana emosi kini bergerak secepat cahaya. Di dunia digital, kesedihan bisa viral hanya dalam beberapa detik. Kemarahan bisa menular lebih cepat daripada klarifikasi. Manusia berubah dari makhluk reflektif menjadi makhluk reaktif. Kita mengomentari sebelum memahami, menghakimi sebelum mempelajari. Telaah akademik menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion, penularan emosi massal yang dipercepat algoritma.
Fenomena inilah yang membuat platform digital tidak lagi menjadi sarana komunikasi, melainkan panggung emosi kolektif. Di sana, luka dipertontonkan, kesedihan menjadi komoditas, kemarahan menjadi konten, dan simpati menjadi valuta sosial. Akibatnya, batas antara ekspresi tulus dan pencitraan menjadi kabur. Banyak orang mempertontonkan diri bukan karena ingin didengar, tetapi karena ingin dilihat. Dan ketika semua orang ingin dilihat, tidak ada lagi ruang yang benar-benar sunyi untuk mendengarkan diri sendiri.
Padahal, dalam kebudayaan kita, keheningan adalah bagian dari kebijaksanaan. Dalam tradisi Islam, ada konsep tadabbur dan tafakkur merenungkan makna sebelum berucap, memahami maksud sebelum bertindak. Dalam kearifan Sunda ada ungkapan ulah kaburu-buru, lamun leumpang kudu neneda—jangan tergesa, setiap langkah butuh doa. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak tumbuh dari kecepatan, tetapi justru dari jeda. Dari kemampuan berhenti sejenak untuk merasakan, memikirkan, dan memahami.
Namun, penting disadari bahwa masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada bagaimana manusia memaknai dan menggunakannya. Media sosial bisa menjadi ruang belajar, ruang inspirasi, bahkan ruang amal. Tetapi tanpa kedalaman refleksi, ia hanya menjadi cermin yang memantulkan kecemasan kita. Kita mengira sedang mencari validasi, padahal sedang kehilangan diri.
Kita mengira sedang berkomunikasi, padahal hanya bersuara tanpa mendengar. Kita mengira sedang terkoneksi, padahal hati kita tercerabut dari keheningan yang menumbuhkan.