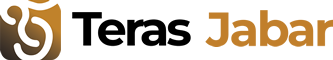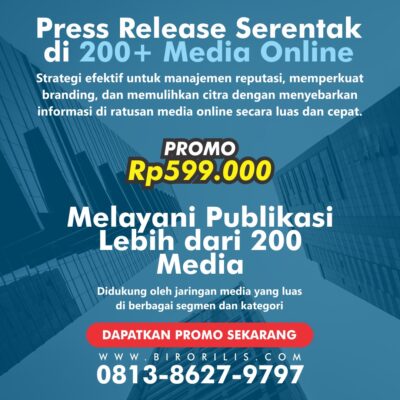Di ranah politik, media sosial memberi ruang baru bagi partisipasi. Gerakan #ReformasiDikorupsi atau #SaveKPK menunjukkan bagaimana isu publik bisa viral dan memaksa pemerintah merespons. Demokrasi menjadi lebih terbuka, setidaknya dalam hal akses dan partisipasi.
Sisi Gelap Algoritma
Namun, janji manis itu datang dengan harga mahal. Dalam ekonomi, budaya konsumtif semakin menguat. Fitur pay later mendorong banyak orang berbelanja barang yang tidak dibutuhkan, berakhir dengan jeratan hutang. Pinjol bahkan menjerat masyarakat dengan bunga tinggi. Bukannya membantu, justru menambah beban.
Dalam politik, algoritma menciptakan polarisasi. Kita hanya melihat konten yang memperkuat pilihan kita. Lawan politik dianggap musuh, diskusi sehat digantikan perang komentar. Demokrasi pun dangkal, lebih mementingkan viralitas ketimbang kualitas gagasan.
Dalam pendidikan, algoritma membentuk generasi yang terbiasa dengan konten instan. Rentang konsentrasi pendek, daya tahan belajar menurun. Guru pun kehilangan sebagian otoritas karena murid lebih percaya pada “guru algoritma” di TikTok atau YouTube.
Dalam kehidupan moral dan agama, algoritma mempercepat degradasi nilai. Budaya instan bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan kesabaran dan proses. Konten negatif—dari ujaran kebencian, pornografi, hingga judi online—mudah sekali menyebar. Algoritma tidak peduli pada nilai, hanya pada keterlibatan (engagement).
Struktur Sosial yang Bergeser
Indonesia sedang menyaksikan lahirnya kelas sosial digital. Mereka yang mampu memanfaatkan algoritma—sebagai kreator konten atau pengusaha online—menikmati keuntungan. Sebaliknya, mereka yang hanya jadi konsumen pasif justru terpinggirkan.
Otoritas sosial juga bergeser. Guru, tokoh agama, bahkan media arus utama kehilangan wibawa. Anak muda lebih percaya pada konten viral dibanding nasihat yang penuh kebijaksanaan. Norma gotong royong dan kesabaran terkikis oleh logika instan dan individualisme algoritmik.