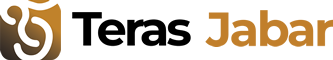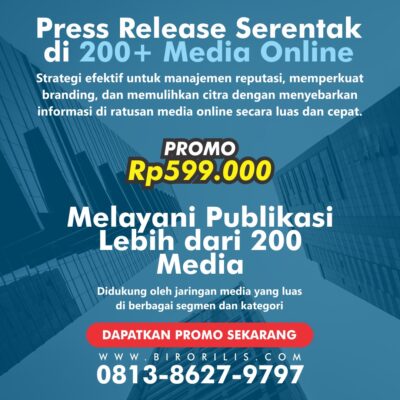Oleh : Subchan Daragana
Pemerhati Sosial / Magister Komunikasi UBakrie
Ada sebuah ironi yang makin terasa di republik ini: pejabat sering merasa dirinya mewakili rakyat, tetapi dalam praktik sehari-hari ia kerap hidup dalam dunia yang berbeda dari rakyat yang diwakilinya. Sebaliknya, rakyat sering dipaksa untuk tunduk pada pejabat, seakan-akan pejabat adalah entitas yang lebih tinggi, bukan pelayan yang semestinya bekerja untuk mereka. Inilah jurang yang semakin lebar—jurang antara rakyat dan pejabat.
Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa politik sejatinya adalah ruang bersama (the public realm), tempat setiap orang hadir dengan kesetaraan untuk membicarakan kebaikan bersama. Namun, realitas komunikasi politik kita justru menyingkapkan paradoks: pejabat berbicara atas nama rakyat, tetapi dengan bahasa yang asing dari keseharian rakyat. Yang muncul bukan dialog, melainkan monolog kekuasaan.
Fenomena ini bukan sekadar soal gaya komunikasi, melainkan menyangkut mentalitas. Komunikasi politik modern menekankan two-way communication, mendengar sekaligus merespons, bukan hanya berbicara. Namun dalam praktiknya, pejabat sering berhenti pada tahap simbolik: hadir di tengah rakyat untuk pencitraan, mendengar aspirasi, lalu mengarsipkannya tanpa menjadi kebijakan nyata. Rakyat pun belajar bahwa suara mereka sering berakhir sebagai formalitas belaka.
Socrates dalam diskursusnya menekankan pentingnya parrhesia—keberanian berkata benar di hadapan kekuasaan. Tetapi di negeri ini, rakyat yang menyuarakan kebenaran sering dicap mengganggu stabilitas. Sementara pejabat yang seharusnya mendengar, justru sibuk dengan narasi keberhasilan dan retorika pembangunan. Inilah yang membuat relasi rakyat–pejabat terbalik: rakyat bukan pejabat, pejabat bukan rakyat.
Jurgen Habermas lewat konsep public sphere menegaskan bahwa demokrasi hidup jika ada ruang diskusi rasional antara pemerintah dan masyarakat. Tapi bagaimana ruang itu bisa hidup, jika komunikasi yang dijalankan hanya satu arah? Kita lebih sering menyaksikan konferensi pers daripada percakapan publik. Lebih banyak monumen pencitraan ketimbang forum partisipasi.
Kondisi ini semakin tajam di era digital. Media sosial membuka ruang ekspresi rakyat, tetapi sekaligus memperlihatkan bagaimana pejabat menggunakan ruang itu untuk menegaskan kekuasaan. Alih-alih berdialog, pejabat membangun buzzer, framing, dan pencitraan digital. Dalam istilah filsafat komunikasi Jean Baudrillard, yang hadir bukan realitas, melainkan simulacra—representasi tanpa substansi. Pejabat terlihat dekat dengan rakyat di layar, padahal dalam kenyataan makin jauh.