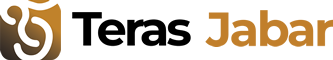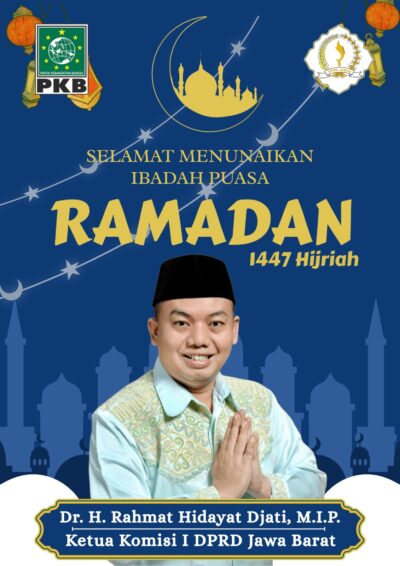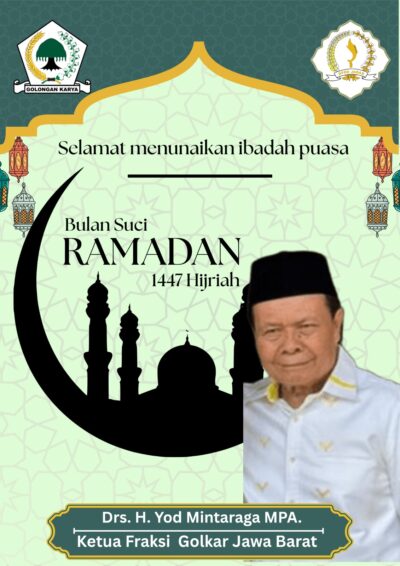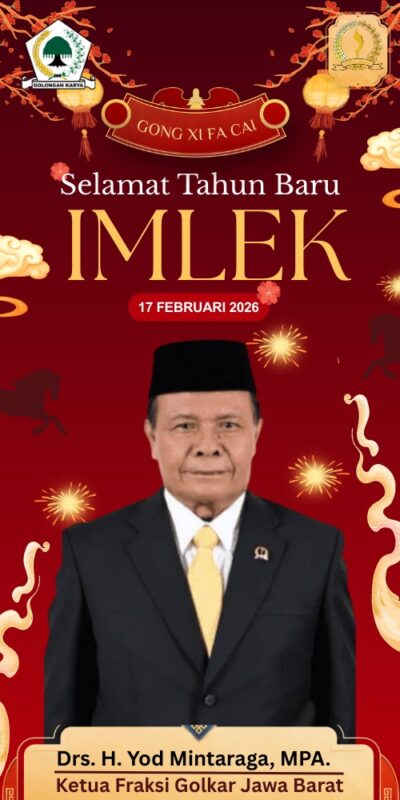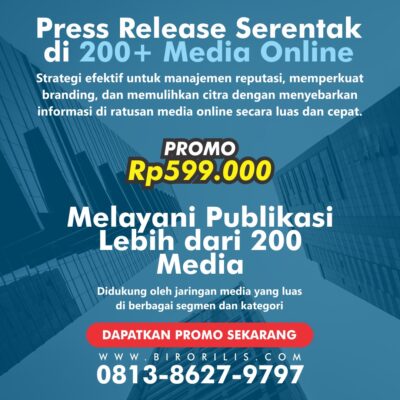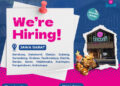Oleh: Subchan Daragana
Pemerhati Sosial – Magister Komunikasi, Universitas Bakrie
Kita hidup di zaman ketika manusia merasa paling terkoneksi, tetapi paling kesepian. Dunia digital yang awalnya disambut sebagai berkah kini perlahan berubah menjadi paradoks, ia mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Di titik tertentu, media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi ekosistem baru yang membentuk cara berpikir, merasakan, mengambil keputusan, bahkan memahami hidup. Pertanyaannya , “apakah media sosial masih menjadi alat kemajuan, atau sedang berubah menjadi mesin perusak yang bekerja dalam kesunyian?”
Para pemikir klasik ekologi media sudah jauh-jauh hari memperingatkan hal ini. Marshall McLuhan dalam tesis terkenalnya ” the medium is the message” mengatakan bahwa teknologi bukan sekadar alat penyampai pesan, melainkan “lingkungan” baru yang perlahan membentuk kesadaran manusia. Neil Postman menambahkannya dengan kritik bahwa kita sedang “menghibur diri sampai mati”, ketika segala hal dijadikan tontonan tanpa ruang untuk refleksi. Sementara Lance Strate menyebut media sebagai lingkungan simbolik yang mengatur ritme hidup, nilai, dan relasi sosial.
Jika dulu televisi dianggap medium paling dominan, kini media sosial telah mengambil alih sebagai “lingkungan baru” tempat pikiran manusia dibentuk. Kita tidak lagi sekadar melihat dunia melalui layar, tapi kita telah hidup di dalamnya.
Banyak dari kita yang tanpa sadar menjalani hidup dengan “refleks ibu jari” menggulir layar ketika bosan, cemas, kesepian, bahkan ketika tidak tahu harus apa. Aktivitas ini tampak sepele, tapi di baliknya ada mekanisme neurologis yang kuat, bahwa setiap notifikasi, like, dan video pendek memicu dopamin. Otak kita menjadi kecanduan stimulasi cepat.
Teknologi mempercepat rangsangan, tetapi memperlambat pemulihan emosi. Akibatnya, muncul generasi yang secara mental selalu tergesa. Mereka terbiasa pada kepuasan instan tetapi gagap menghadapi proses panjang. Mereka mahir mengekspresikan opini, tetapi kesulitan bertahan dalam percakapan mendalam. Mereka pandai berkomentar, namun miskin kontemplasi. Kita menyebut fenomena ini sebagai ” ghaflah modern”, kelalaian gaya baru yang tidak lagi disebabkan kealpaan spiritual, tetapi dirancang oleh arsitektur algoritma.
Di banyak rumah, layar ponsel menjadi sumber keretakan kecil yang tak disadari. Pasangan berbicara tanpa saling mendengarkan. Anak merasa hadir secara fisik, tetapi tidak dihargai secara emosional. Waktu keluarga terpecah oleh jeda notifikasi. Komunikasi berubah menjadi sekadar pertukaran kalimat, bukan kehadiran batin. Para psikolog menyebut ini “presence erosion”, erosi kehadiran manusia.
Bandung, sqlah satu kota yang dikenal sebagai kota kreatif, juga menghadapi paradoks ini. Di satu sisi warganya produktif menghasilkan konten, kolaborasi, inovasi digital. Namun di sisi lain, kecemasan sosial meningkat, konflik di ruang maya meluber ke ruang nyata, dan banyak remaja tumbuh dalam tekanan perbandingan sosial yang tidak sehat.
Nilai moral pun ikut digeser oleh apa yang viral, bukan oleh ” apa yang benar “. Apa yang dulu diajarkan guru dan orang tua kini kalah oleh apa yang trending.
Media sosial memaksa kita mengikuti arus dunia yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kita dihadapkan pada tekanan agar selalu hadir, selalu update, selalu terlihat. Orang berkompetisi untuk bahagia, bukan untuk berkembang. Dalam lanskap seperti ini, ukuran hidup tidak lagi diukur oleh kebenaran moral, tetapi oleh algoritma. Kita sedang hidup dalam sebuah republik baru, “republik algoritma”, yang kepemimpinannya tidak pernah kita pilih.
Namun, tidak adil jika kita hanya menyalahkan teknologi. Masalah muncul ketika manusia kehilangan kendali, ketika alat yang seharusnya membantu justru menjadi penentu hidup. Karena itu, sejumlah negara mulai bergerak. Tiongkok membatasi jam penggunaan media sosial bagi remaja. Singapura menerapkan algoritma transparency dan hukum anti-disinformasi. Australia memperketat regulasi keselamatan online. Semuanya sepakat bahwa media sosial butuh aturan, bukan dibiarkan liar.
Indonesia belum terlambat, tetapi waktunya tidak banyak. Melihat maraknya judi online, maraknya konten kekerasan, polarisasi politik, hingga krisis kesehatan mental remaja, kita membutuhkan arah baru dalam governance digital. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tetapi sebagai penjaga ekosistem.
Di level pribadi, kita pun butuh puasa digital ( diet digital ), kemampuan menjauh sejenak untuk memulihkan kedalaman batin. Kita perlu membangun media diet, memilah informasi, mengatur waktu layar, dan kembali merawat ruang offline. Masjid, ruang kelas, ruang keluarga, ruang komunitas, semua tempat yang memulihkan kembali fitrah manusia.
Karena pada akhirnya, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam ruang yang penuh kecepatan dan kebisingan. Fitrah manusia membutuhkan keheningan, perjumpaan, dan kehadiran. Dunia digital hanyalah alat. Ia dapat menjadi ladang amal, dapat pula menjelma jurang kehampaan. Kita yang menentukan.
Jika kita ingin masa depan Bandung dan Indonesia tetap beradab, kita perlu memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan kemanusiaan. Media sosial harus kembali menjadi alat kemajuan, bukan mesin perusak sunyi yang menggerus batin kita perlahan.
Kemenangan terbesar bukanlah viralitas, tetapi kemampuan mempertahankan diri sebagai manusia di tengah gempuran algoritma.***