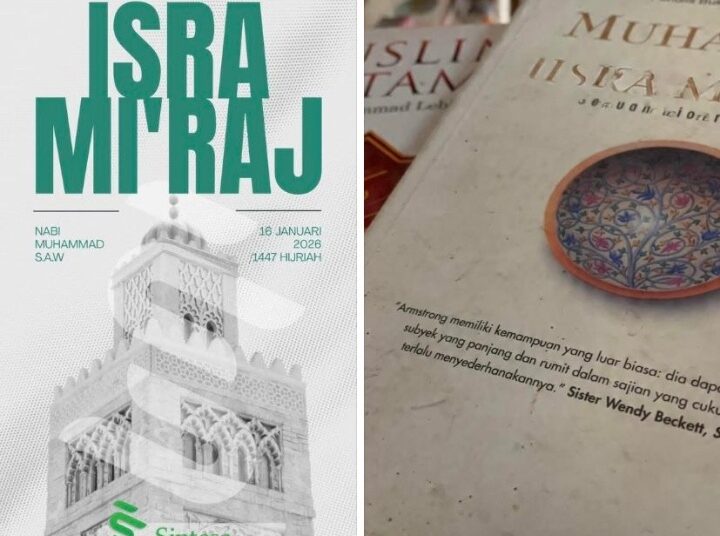Al-Quran menyinggung peristiwa ini dalam Surah Al-Isra ayat 1, meski dalam tradisi tafsir klasik sering dikaitkan pula dengan ayat-ayat lain seperti Al-Baqarah yang menekankan pentingnya iman terhadap hal-hal gaib.
Tafsir semiotika terhadap Isra Miraj membuka ruang untuk melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai pengalaman spiritual, tetapi juga sebagai sistem tanda yang sarat makna, di mana perjalanan Nabi menjadi kode simbolik tentang transendensi, legitimasi kenabian, dan hubungan antara bumi dan langit.
Dalam sirah klasik, Ibnu Katsir menekankan aspek mukjizat dan keagungan spiritual yang meneguhkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir.
Sementara para penulis dan pengkaji modern seperti Martin Lings dalam Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources(revisi 1991), Tor Andrae, Muhammad Husain Haekal, Karen Armstrong, hingga Lesley Hazleton dalam The First Muslim(2013), serta Juan Cole dalam Muhammad: Prophet of Peace Amid the Clash of Empires(2018), mencoba membaca Isra Miraj dalam konteks historis, psikologis, dan sosial.
Mereka melihat bahwa peristiwa ini tidak hanya mengandung dimensi religius, tetapi juga pesan moral dan politik: tentang pentingnya keadilan, kedamaian, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Orientalis sejak masa Perang Salib pertama tahun 1096, di antaranya Raymond IV dari Toulouse, Godefroy de Bouillon, Robert Curthose, Bohemond dari Taranto, dan Adhemar dari Le Puy, sering tergoda untuk menafsir Isra Miraj dengan rasio semata, mempertanyakan kemungkinan fisik perjalanan tersebut.
Namun dalam telisik semiotika, sebagaimana dikembangkan, dua di antaranya, Roland Barthes dan Umberto Eco, Isra Miraj dapat dipahami sebagai teks simbolik yang mengandung tanda-tanda atau sejumlah kode, sakral maupun profan.
Masjidil Haram melambangkan asal-usul spiritual, Masjidil Aqsa sebagai simbol keterhubungan dengan tradisi kenabian sebelumnya, dan Sidratul Muntaha sebagai tanda batas pengetahuan manusia sekaligus puncak pengalaman transendental.
Dengan hermeneutika Qur’an(Al-Kitab) yang dikembangkan oleh pemikir awal hermeneutik klasik seperti Sibawaihi atau „Si Wangi Apel“ alias Abu Bisyr Amr bin Utsman bin Qanbar al-Bishri(765-796), peristiwa ini dapat dibaca sebagai kode yang menghubungkan iman, sejarah, dan simbol-simbol universal.