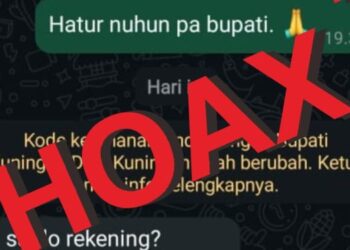Oleh: Subchan Daragana
Pemehati Sosial / Magister Komunikasi Universitas Bakrie
( Mengembalikan Ponsel sebagai Alat, bukan tujuan )
Kita hidup di zaman yang aneh sekaligus sunyi. Manusia tidak lagi menyembah patung, tetapi layar. Tidak bersujud di sajadah, melainkan menunduk pada ponsel. Tanpa disadari, lahir “agama baru” yang tak punya masjid, tak punya kitab suci, namun memiliki jutaan pengikut setia. Namanya, “agama algoritma”, Tuhannya ponsel, Surganya validasi/ perhatian.
Setiap hari kita bangun bukan untuk menenangkan jiwa, melainkan mengecek notifikasi. Jempol lebih dulu bergerak sebelum hati sempat bertanya. Takut ketinggalan kabar, takut tak relevan, takut tak terlihat. Inilah FOMO fear of missing out, ritual harian umat digital. Kita scrolling bukan karena butuh, tapi karena gelisah jika tidak ikut arus.
Al-Qur’an sudah lama mengingatkan fenomena ini, jauh sebelum ponsel ditemukan. “Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya?” (QS. Al-Jatsiyah: 23). Hari ini, hawa nafsu itu tak selalu berupa syahwat biologis, tetapi syahwat eksistensi, ingin diakui, ingin dilihat, ingin dianggap penting. Like, komentar, dan views menjadi semacam “pahala instan” yang menenangkan sesaat, lalu menuntut lagi.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, inilah kerja algoritma yang sangat sistematis. Media sosial tidak netral. Ia bekerja dengan logika agenda setting menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Apa yang sering muncul di layar, perlahan dianggap bernilai. Apa yang jarang terlihat, perlahan dilupakan. Kesalehan yang sunyi kalah bersaing dengan sensasi yang bising. Kedalaman kalah oleh kecepatan.
Kita tidak lagi memilih konten secara sadar, kitalah yang dipilih oleh konten. Algoritma membaca kebiasaan kita, lalu menyuapi apa yang membuat kita betah berlama-lama. Bukan yang menenangkan, tapi yang memicu emosi. Marah, iri, takut, bangga, semua jadi bahan bakar atensi. Di titik ini, manusia bukan lagi pengguna, melainkan komoditas.
Rasulullah ﷺ pernah bersabda, “Akan datang masa di mana orang yang paling sabar dalam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.” (HR. Tirmidzi). Bara api hari ini bukan pedang atau penjara, melainkan godaan untuk selalu hadir di dunia maya. Menahan diri untuk tidak pamer. Tidak ikut hujat. Tidak larut dalam hiruk-pikuk. Ternyata menjaga iman di era digital sama beratnya dengan mempertahankan keyakinan di masa penindasan.